
Kami Melukis Karena Itulah HeRe Ada
Hendra Harsono dan Restu Ratnaningtyas menyambut dari dalam rumah, pasangan muda ini tinggal di sebuah rumah kecil yang juga berfungsi sebagai studio. Studio Hendra Harsono (HeHe) mengambil tempat yang dulunya adalah ruang tamu sedang Restu Ratnaningtyas mengambil tempat sedikit memojok, di dinding berdampingan dengan ruang jemur.
Hendra Harsono
Lukisan Hendra Harsono (26 th) atau kerap dipanggil HeHe, merupakan kumpulan figur yang digabungkan dalam satu bidang kanvas bujur sangkar. Objek utama yang kemudian dikelilingi oleh objek pendukung yang lebih kecil. Objek-objek pendukung bisa berupa teks, atau semata bidang-bidang yang kemudian diisi warna-warna terang. Objek-objeknya kebanyakan berupa mahluk serupa manusia, bertangan, berkaki, sering kali bermata lebih dari satu, bermulut ekstra lebar dan juga beberapa menggenakan topeng. Kumpulan figur yang sekarang lazim disebut dengan karakter itu, sesungguhnya tidak membentuk sebuah cerita yang utuh. Mereka sekedar dijejerkan, seperti kumpulan boneka di toko boneka. Kalau kemudian ada judul, yang seolah-olah mewakili sebuah kisah, itu tak lebih adalah “kesimpulan” yang terbentuk secara tidak sengaja. HeHe tidak berangkat dari cerita seperti yang awalnya saya duga. Dia pelukis dekoratif, seperti Widayat yang suka menggambar bentuk aneh kemudian mengisi semua bidang kanvasnya dengan torehan cat berwarna gelap. Sriwarso Wahono menyebut lukisan Widayat sebagai dekora-magis, mungkin disebabkan oleh kesenangan menghias dan warna tanah nan gelapnya sehingga terlihat “magis”. Saya tergoda untuk menyebut karya HeHe dengan julukan yang sama, tapi saya kira itu tidak tepat. Pertama julukan dekoratif itu pada tataran seni rupa di barat adalah julukan “penghinaan” dan hanya di berikan kepada pada para pelukis kerajinan di art shop atau kepada para pelukis rakyat (folk artist), kedua konteks ketika karya HeHe dibuat berbeda dengan Widayat. Konteks karya-karya Widayat adalah semangat dari pencarian “jati diri lukisan nasional” yang sejalan dengan faham Orde baru yang apolitis. Maka munculnya lukisan yang ramai dengan isen-isen dan tanpa kritik sosial seperti lukisan (katakanlah) LEKRA adalah keniscayaan. Pelukis-pelukis jaman itu menyembunyikan ketaklukannya di dalam hutan rimba isen-isen dan belukar hiasan nan rumit. Dekoratifisme adalah salah satu cara untuk cari selamat dan strategi bertahan hidup yang kemudian diterima sebagai jati diri “seni lukis” nasional ala Orde Baru.
Oleh karena HeHe hidup dalam jaman berbeda, maka ketakutan itu sesungguhnya tidak ada, sudah hanyut disapu banjir reformasi. Lalu apa yang membuat dia membuat lukisan “dekoratif” seperti itu?
Sesungguhnya HeHe adalah bagian dari generasi baru perupa-perupa muda yang membawa gerbong seni jalanan (street art-ism), sebuah bahasa rupa yang banyak menggabungkan kaligrafi, ilustrasi, dan seni komik. Bahasa rupa ini berkembang sejak lima tahun terakhir terutama di Yogyakarta dan belum ada yang membahas secara utuh. Kalaupun ada pembahasan, itu merupakan pengantar katalog yang biasanya tidak cukup memadai untuk mengungkapkan fenomena ini. Jadi, sering kali yang muncul kemudian adalah penyerderhanaan atau perumitan tergantung sudut pandang para penulisnya. Penulis muda cenderung memujanya sebagai lahirnya gaya baru seni rupa Yogyakarta, penulis yang lebih senior menganggap bahasa rupa ini adalah sebuah tiruwagu (copycat) dari gaya street art yang berawal di Amerika lewat gerakan Low Brow-nya.
HeHe jelaslah pengagum gerakan Low Brow ini seperti halnya teman-teman angkatannya (Uji Handoko, Iwan Effendi, Dicky leos, dan beberapa lainnya), seperti halnya mereka adalah pengagum dari Eko Nugroho muda [1]dengan senirupa plesetannya. Para perupa muda itu memang mempunyai metode kerja yang berbeda dengan angkatan sebelumnya. Mereka bekerja tanpa “pesan” atau jargon politik apapun. Mereka adalah produk Orde Baru yang paling wahid. Sekelompok generasi apolitis yang bekerja dengan spirit main-main yang kuat. Tanpa perlu membungkus kerja mereka dengan jargon apapun, bekerja hanya untuk senang-senang. Oleh karena spirit itulah maka hampir tidak pernah muncul persoalan jika ada banyak kemiripan antara karya mereka para aktifis seni jalanan di “Barat”. Padahal pada angkatan sebelumnya kemiripan ini adalah “bencana” karena mereka dianggap sebagai peniru, seringkali juga di sebut sebagai “beo” isme. Ketidak pedulian itu bisa jadi muncul karena mereka tidak merasa bahwa meniru itu adalah pamali di seni rupa kotemporer. Atau dengan kata lain meniru itu pun ada “seni”nya. Tidak bisa semata-mata sama dan serupa, akan tetapi membutuhkan keahlian juga. Dan sering kali fase peniruan ini adalah fase awal dari karier seorang perupa, sebelum kemudian waktu dan kerja keras membentuk identitas baru mereka.
Hanya saja persoalan di luar proses kreatif seorang seniman sering kali lebih dominan dibandingkan persoalan kreatif itu sendiri. Pasar yang lapar tidak pernah mau bersabar untuk menunggu seorang seniman muda berproses untuk mendapatkankan bentuknya sendiri lewat serangkaian pengaruh dari seniman yang mereka kagumi. HeHe dan Restu harus berjuang untuk menarik jarak dari pengaruh itu. Mengambil dan mengolahnya kembali untuk bisa menemukan sebuah bahasa yang khas darinya.
Mencari Untuk Entah[2]
Pergulatan dan pancarian itu memang nampak pada karya-karya HeHe sekarang, dibandingkan dengan karya pada pameran tunggal sebelumnya kita bisa menemukan sedikit perbedaan. Pada pameran tunggal pertamanya, karya-karyanya masih didominasi objek tunggal yang mengambil nyaris seluruh ruang kanvas, sekarang perbedaan itu nampak pada munculnya isian-isian (isen-isen) yang berupa bidang geometris, serpihan-serpihan, dan bidang-bidang warna. Dalam lukisan batik isen-isen adalah gambaran mikroskopik dari dunia. Dunia agraris yang terdiri dari hutan, sawah dan satwa diterjemahkan dalam jutaan garis dan titik yang membentuk bentuk-bentuk biomorfik. Isen-isen adalah inti dari batik. Tanpa isen-isen yang jlimet objek utamanya menjadi tak nampak.
Restu Ratnaningtyas
Di pojok ruang makan,studio Restu Ratnaningtyas atau Restu (28 th) terletak. Rumah kecil itu memang terbagi menjadi dua studio yang masing-masing dibatasi oleh pembatas imajiner; pantry. Restu nampak nyaman dengan studio kecilnya. Gambar sketsa rancangan karya dan kartu pos tertempel di kulkas tak jauh dari sudut studionya. Sebuah sudut yang aktif. Berbeda dengan Hehe, Restu adalah seorang pendongeng. Lukisannya adalah sebuah buku cerita besar. Pada lukisanya kita selalu menemukan sebuah benda kecil yang selalu mengawali cerita itu. Kaleng sarden, di “Aku Ingin Hidup seribu Tahun lagi”, (akrilik di atas kanvas, 2009), botol minyak gosok, di “ Dan kita masih saja…” (akrilik di atas kanvas, 2009) dan lain sebagainya. Objek kecil itu menjadi “pusat perhatian” karena penggunaan warna kuat yang mencolok dan pengerjaannya yang detil dan selalu ditempatkan pada bagian tengah lukisan. Memang salah satu kelebihan Restu adalah kemampuannya untuk bercerita lewat benda sederhana dan sehari-hari. Dia tampak sangat menikmati fantasi yang terbentuk dari benda-benda sederhana itu.
Restu memperoleh pendidikan seni dari sekolah untuk mendidik guru kesenian di Jakarta. Sekolah semacam ini selalu dianggap semenjana dalam jagad seni rupa, sekolah untuk menjadi seniman (dan) bisa jadi guru yang nanggung pula. Situasi semacam ini sesungguhnya membuat sebagian mahasiswanya yang kemudian memutuskan untuk menjadi seniman profesional harus bekerja lebih keras. Mereka harus membuktikan bahwa mereka mampu menjadi seniman seperti rekan-rekan mereka yang belajar di sekolah “khusus” seniman.
Sebelum bekerja sebagai pelukis profesional, Restu juga pernah bekerja sebagai seorang kurator dan penggerak ruang alternatif di Jakarta. Sebelumnya dia bahkan pernah menjadi seorang penggambar teknis untuk sebuah perusahaan pengangkut harta karun. Pengalamannya itu bisa jadi membuat dia punya cukup cerita untuk didongengkan, dan secara tidak langsung mempengaruhi cara dia mengeksekusi karya-karyanya.
Lukisan Restu sekarang bercerita tentang pengalamannya sehari-hari, setelah menikah dan migrasi ke Yogyakarta. Lukisan-lukisannya adalah gambaran dari proses belajar di kehidupan baru. Dari seorang perempuan mandiri yang hilir mudik dengan bis kota menjadi perempuan rumahan yang mobilitasnya tergantung orang lain. Rendahnya mobilitas itu membuat dia sibuk dengan persoalan sekitar rumah; orang kerokan, kepanasan, dan lain sebagainya. Akan tetapi persoalan sehari-hari itu kemudian diolah sedemikian rupa menjadi sebuah dunia yang berbeda. Perempuan yang teronggok di sudut dapur menggunakan fantasinya untuk menjelajah dunia luar, semacam kompensasi dari ketidakmampuannya menjelajah dunia urban Jogja secara ragawi.
Lukisan “Here’s Dad and He’s Gone Wild” (akrilik di atas kanvas, 2009) adalah parodi dari keluarga harmonis ala Khong Guan Biskuit, dengan imbuhan Nintendo DS. Di latar belakangnya seorang kelinci sibuk memotong tangannya sendiri di atas meja dapur sementara sebuah kipas angin mengintip dari luar jendela. Tokoh kelinci itu adalah penghubung cerita dari mainan yang dimainkan oleh anak laki-laki, sekaligus memperlihatkan sebuah koneksi dari dunia main-main, dunia game yang diwakili oleh si kelinci dan gadget itu sendiri. Kelinci meski membelakangi objek utama akan tetapi matanya menoleh ke arah penonton, seperti meminta perhatian. Bahasa tubuh kelinci demikian itu membuat penonton kemudian fokus pada tangan yang terpotong-potong bagai timun. Sebuah rangkaian cerita yang berlapis-lapis.
Sementara itu pada lukisannya yang lain, Restu gagal mereka fantasi seperti lukisan-lukisannya kemudian. Lukisan itu berjudul ”Malam Tidak Bisa Menyembunyikan Cahaya Untuk Kita Lagi” (akrilik di atas kanvas, 2009). Lukisan ini mencoba untuk membebaskan pikirannya dari sebuah konstruksi cerita. Dia sepertinya ingin meniru metode Hehe yang selalu memulai dari figur. Lukisan ini akhirnya berhenti pada gugusan figur-figur yang “pecah”, karena tidak adanya korelasi antar figur-figur itu. Bagi Restu figur tidak pernah bisa berhenti sendiri, mereka adalah sebab dan akibat. Restu memang harus menyadari bahwa kekuatannya bukan pada pembentukan figur atau karakter yang aneh seperti Hehe, kekuatannya ada pada kemampuannya menjalin cerita, karena dia adalah seorang pendongeng.
HeRe
HeRe adalah sebuah proyek kolaborasi antara Restu dan Hendra. Dalam sebuah proyek kolaborasi yang terpenting adalah bagaimana masing-masing pihak mau mengambil peran secara aktif, sekaligus menjadi pasif jika memang dibutuhkan. Posisi tarik ulur inilah yang membuat proyek kolaborasi ini jarang dilakukan oleh para perupa yang punya ego sebesar gunung.
HeRe adalah dunia main-main dari pasangan seniman ini. Di sini mereka terbebas dari cap dagang Hendra Harsono dan Restu Ratnaningtyas yang sering kali membungkus mereka dengan berbagai atribut; seniman muda, low brow artist, street art ism, dan lain sebagainya. Dengan menciptakan He Re maka lahirlah boneka kertas, dan rumah boneka. HeRe adalah sebuah terobosan atas sebuah cap yang mapan. HeRe terlihat lebih santai, tanpa beban, dan lebih eksploratif, mungkin karena mereka mampu mengambil jarak dari karya mereka sebelumnya sehingga lahirlah karya-karya seperti itu.
Rumah Boneka ;“The Intruders” (karton, lampu, akrilik, 2009) adalah salah satu contohnya. Karya ini lahir setelah mereka “muak” dengan bidang-bidang datar dari kain kanvas. Rumah boneka yang dibuat dari kardus seperti sebuah suaka bagi mereka. Bermain dengan kertas dan membentuknya menjadi objek kecil trimatra, kemudian meletakkan dalam dunia mini yang mereka bentuk serupa sebuah kotak teve, lengkap dengan lampu kelap-kelip di dalamnya. Bermain dengan material yang murah dan sederhana adalah salah satu ciri yang menonjol pada karya street art di Barat. Ciri ini hilang atau tidak sempat diadopsi oleh anak-anak muda yang meniru gaya itu di Jogja. Karya-karya trimatra mereka kebanyakan terbuat dari serat kaca dan sebagian malah telah mencetaknya dengan logam. Dengan bermain memakai benda yang murah HeRe kembali meletakan spirit seni jalanan ini ke habitatnya; art poverta, seni (bermedia) murah seni rupa untuk “semua” orang. HeRe juga memberi wajah baru bagi karier seniman mereka berdua, sebuah wajah yang anonim, sebuah alias. Identitas baru tempat mereka sembunyi dari dunia senirupa yang mapan yang cepat menjadi tua.
Bermain dengan material yang murah dan sederhana adalah salah satu ciri yang menonjol pada karya street art di Barat. Ciri ini hilang atau tidak sempat diadopsi oleh anak-anak muda yang meniru gaya itu di Jogja. Karya-karya trimatra mereka kebanyakan terbuat dari serat kaca dan sebagian malah telah mencetaknya dengan logam. Dengan bermain memakai benda yang murah HeRe kembali meletakan spirit seni jalanan ini ke habitatnya; art poverta, seni (bermedia) murah seni rupa untuk “semua” orang. HeRe juga memberi wajah baru bagi karier seniman mereka berdua, sebuah wajah yang anonim, sebuah alias. Identitas baru tempat mereka sembunyi dari dunia senirupa yang mapan yang cepat menjadi tua.Selamat menikmati Restu ratnaningtyas, Hendra “HeHe” Harsono dan HeRE sang liyan-nya.
[1] Eko Nugroho sekarang menggunakan pendekatan yang berbeda. Dia menggunakan eksotisme Jawa seperti halnya perupa tahun 80-an (Heri Dono misalnya) semacam wayang kulit gaya baru. saya tidak tahu apakah bahasa Eko yang “baru” ini juga menarik minat perupa angkatan dibawah Eko semacam HeHe dan kawan-kawannya.
[2] Di adaptasi dari film yang dibuat oleh Wimo Ambala Bayang, yang berjudul Berlari Untuk Entah.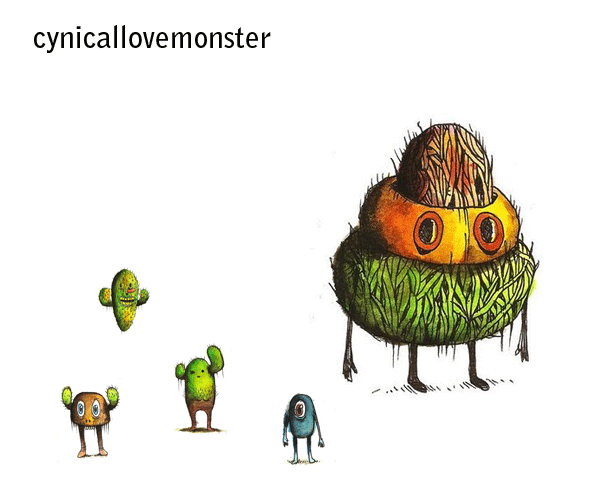



1 comment:
Owh....tuhan memberkati artwork kalian.....
ide yang segar denagn kenangan lama dan sederhana dari mulai ilustrasi kaleng nissin hinga kerokan...
:D
Post a Comment